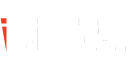Indonesia telah menyampaikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional yang tertera dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada tahun 2022. Dalam implementasi ENDC tersebut, peran daerah menjadi sangat penting, utamanya pada sektor energi, karena banyak sumber energi terbarukan yang terdapat pada skala daerah. Misalnya seperti wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki potensi energi terbarukan, namun masih bergantung pada dieselguna memenuhi kebutuhan listrik di provinsi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memperhitungkan peran daerah dalam upaya pencapaian target NDC.
Menanggapi hal ini, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) bekerja sama dengan Yayasan Pikul telah melaksanakan diskusi terbatas pada 4 Oktober 2024, di Kupang, NTT untuk memaparkan hasil rangkaian diskusi multipihak yang telah dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus 2024. Dari diskusi tersebut, terdapat beberapa temuan yang dapat dijadikan masukan bagi proses perencanaan dan implementasi aksi iklim di Provinsi NTT yang juga bermanfaat bagi pemerintah pusat.
Emisi Tercatat dan Potensi Penurunan Emisi di Provinsi NTT
Berdasarkan data pelaporan emisi Provinsi NTT yang tercatat dalam aplikasi Sign-Smart, sektor pertanian menjadi sektor yang paling banyak melaporkan inventaris emisi GRK-nya. Namun, sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait apakah pelaporan tersebut memang sudah mencakup semua data di masing-masing sektor, bagaimana cara melaporkannya, dan bagaimana menghitung data pelaporan tersebut.
Terkait potensi penurunan emisi NTT yang tercatat dalam aplikasi AKSARA, sampai tahun 2022 terdapat sekitar 580 kegiatan penurunan emisi di Provinsi NTT yang terlaporkan dalam aplikasi tersebut. Namun, kegiatan tersebut hanya didominasi oleh sektor energi, misalnya seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilakukan Pemerintah melalui dana alokasi khusus.
Menyinggung isu energi di NTT, sejauh ini ternyata isu tersebut tidak hanya seputar distribusi energi saja, melainkan juga akses dan infrastruktur energi. Meskipun rasio elektrifikasi desa di NTT telah mencapai 93%, namun hanya 63% total rumah tangga yang telah teraliri listrik (Presentasi PIKUL, 2024). Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu:tingginya ketergantungan pada energi fosil; serta pemetaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang masih rendah.
Hambatan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Aksi Iklim
Berdasarkan rangkaian diskusi tersebut, ditemukan lima faktor lain yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi-aksi iklim di daerah, antara lain:
- Kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang jelas dan tumpang tindih
Hambatan ini terjadi pada sektor energi dan energi terbarukan. Sebagai contoh, adanya Undang-Undang (UU) sektor energi, seperti UU Kelistrikan dan UU Panas Bumi, yang telah memperkuat dominasi provinsi sebagai perpanjangan tangan pusat, dan tidak memberikan kewenangan signifikan bagi kabupaten/kota. Hal tersebut telah menciptakan disinsentif bagi daerah untuk berkontribusi dalam implementasi NDC, sehingga diperlukanpenataan kewenangan yang lebih adil dengan pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, khususnya untuk sektor energi terbarukan.
- Keterbatasan pendanaan bagi daerah untuk berkontribusi optimal dalam pencapaian NDC sektor energi
Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) tersedia, namun dalam hal penggunaan masih sangat spesifik dan tidak memberikan keleluasaan bagi daerah untuk berinovasi dalam mengatur penggunaannya. Selain itu, adanya keterbatasan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) membuat alokasi dana untuk feasibility study (FS) guna pengembangan energi terbarukan juga tidak tersedia. Oleh karena itu, perlu dukungan pendanaan spesifik dari DAK untuk mencapai target NDC di sektor energi, termasuk untuk fase FS. Pengembangan skema pendanaan inovatif juga penting dilakukan, seperti pendanaan yang dapat diakses melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
- Pemantauan dan evaluasi pengurangan emisi GRK pusat dan daerah yang belum terintegrasi
Sistem pemantauan dan evaluasi pengurangan emisi GRK yang belum terintegrasi dengan baik antara pusat dan daerah dapat mempersulit pengukuran kemajuan dan akuntabilitas pencapaian NDC. Hal ini ditambah juga dengan banyaknya platform dan mekanisme pelaporan yang berbeda, data baseline emisi GRK antara pusat dan daerah yang belum selaras, serta kewajiban alur pelaporan dan data terkait emisi GRK yang masih belum jelas. Maka, dibutuhkan platform data dan sistem pelaporan terintegrasi yang mencakup semua sektor dan level pemerintahan sebagai solusinya.
- Rendahnya kapasitas dan pemahaman tentang perubahan Iklim di tingkat daerah
Terbatasnya pemahaman para stakeholder tentang perubahan iklim, NDC, dan strategi penurunan emisi GRK menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi program mitigasi dan adaptasi. Hal ini disebabkan karena akses terhadap informasi dan teknologi ramah lingkungan di daerah masih terbatas. Kapasitas pemerintah daerah dalam merancang program mitigasi dan adaptasi yang sesuai dengan konteks lokal juga masih rendah. Maka dari itu, diperlukan penguatan kapasitas melalui program edukasi perubahan iklim, baik untuk pemerintah daerah maupun stakeholder terkait.
- Lemahnya koordinasi dan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah
Hal ini menyebabkan efektivitas program dan sinergi antar stakeholder dalam pencapaian NDC menjadi terhambat. Kelembagaan di tingkat daerah untuk isu perubahan iklim pun masih lemah dan kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim di NTT juga masih terbatas. Pengembangan platform koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu dilakukan lebih baik lagi untuk memperkuat koordinasi, termasuk mengoptimalkan peran Pokja Perubahan Iklim.
Peran BPDLH dalam Mendukung Peningkatan Aksi Iklim Daerah
Saat ini, BPDLH telah memiliki lima program yang menjadi arahan pengelolaan dana, yaitu Forestry and Land Uses (FOLU) dan keanekaragaman ekosistem; energi baru, terbarukan, bersih dan terjangkau; konsumsi dan produksi berkelanjutan; kesehatan, air, dan ketahanan pangan; serta adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana. Selain itu, BPDLH juga memiliki program pendanaan untuk pengembangan start-up. Meski demikian, pendanaan BPDLH masih memiliki keterbatasan. Misalnya, saat ini dana yang ada di BPDLH baru terfokus pada sektor lahan saja, sedangkan untuk isu energi masih sedikit yang bisa dikelola, termasuk dana untuk melakukan feasibility study.
Selain itu, Provinsi NTT sudah mendapatkan alokasi dana dari kegiatan berbasis lahan, yaitu REDD+ yang dapat digunakan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi. Namun, Pemerintah Provinsi NTT perlu mengajukan program melalui penyusunan proposal terlebih dahulu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu kepada rencana kerja provinsi. Kemudian, proposal tersebut yang nantinya akan dipertimbangkan dan diproses untuk memperoleh alokasi dana FOLU. Mekanisme tersebut diharapkan mampu membantu Provinsi NTT guna meningkatkan aksi iklimnya dalam rangka mencapai target . (NZE).
Share: