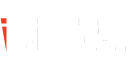Persetujuan Paris pasal 14 menyatakan bahwa para Pihak harus melakukan inventarisasi terhadap implementasi Persetujuan Paris untuk menilai seberapa jauh upaya-upaya para Pihak secara kolektif dalam mencapai tujuan dari Persetujuan Paris. Inventarisasi yang dilakukan mencakup aksi dan bantuan iklim yang telah dilakukan, mengidentifikasi kesenjangan serta menyusun rencana kerja sama guna mempercepat aksi iklim. Proses ini disebut sebagai Global Stocktake (GST).
GST pertama dilakukan pada tahun 2023 bertepatan dengan Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA) ke-5 di Dubai, Uni Emirat Arab, dan harus dilakukan setiap lima tahun. Hasil GST diharapkan dapat memberi informasi kepada pembuat keputusan (policymakers) dan pemangku kepentingan (stakeholders) guna melihat kembali serta meningkatkan komitmen para Pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Nationally Determined Contributions (NDC).
Hasil GST pertama mengakui bahwa aksi-aksi iklim yang disampaikan oleh para Pihak dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan Persetujuan Paris. Misalnya, ketiadaan NDC menyebabkan kenaikan temperatur rata-rata global akan berada pada jalur 4 °C; sedangkan apabila NDC yang disampaikan para Pihak diterapkan seluruhnya, maka kenaikan temperatur rata-rata global akan berada pada jalur 2,8 °C (paragraf 18, Decision 1/CMA.5). Berdasarkan hal tersebut, pada GST1, para Pihak sepakat untuk memperkuat aksi iklim secara kolektif, melalui beberapa aksi. Misalnya, pada sektor energi, para Pihak sepakat untuk meningkatkan ambisi dan mempercepat aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui, diantaranya, transisi energi dengan melipatgandakan hingga tiga kali kapasitas energi terbarukan secara global serta menggandakan efisiensi energi pada tahun 2030, beralih dari bahan bakar fosil, serta menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi darat.
Sebagai tindak lanjutnya, sesuai dengan kesepakatan para Pihak di GST, maka para Pihak diharapkan untuk menyampaikan Second NDC (SNDC) pada secepat-cepatnya bulan November 2024, dan selambat-lambatnya Februari 2025. Indonesia pun tidak terkecuali.

Antara Swasembada dan Konsekuensinya
Pada masa kepresidenan ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki 8 misi yang disebut sebagai Asta Cita. Misi tersebut di antaranya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional. Guna mencapai swasembada pangan, Presiden Prabowo mendorong untuk melanjutkan program pengembanganlumbung pangan (food estate), yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, food estate ini akan dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan sebagai lokasi prioritas, serta 10 wilayah lainnya. Pengembangan food estate ini menargetkan 4 juta hektar sawah dan tambahan produksi beras sebesar 10 juta ton, guna meningkatkan produksi dan luas panen padi.
Sementara itu, swasembada energi akan dicapai melalui program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit, serta pengembangan bioetanol dari singkong dan tebu. Dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro pada November 2024, Presiden Prabowo mengumumkan penerapan kebijakan biodiesel B50 pada 2025, di mana 50% dari bahan bakar diesel tersebut berasal dari biofuel berbasis kelapa sawit. Biodiesel berbasis kelapa sawit dinilai dapat mengurangi emisi GRK, di mana perkebunan kelapa sawit berperan dalam menyerap emisi sebesar 64 ton CO2-ek per hektar per tahun. Oleh karena itu, penerapan kebijakan B50 diharapkan berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan. Guna mencapai tujuan dari kebijakan ini, produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) yang diperlukan setidaknya membutuhkan 9,2 juta hektar lahan.
Swasembada pangan dan energi memang penting untuk ketahanan suatu negara. Melalui swasembada, negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, mengurangi ketergantungan pada negara lain, serta memperkuat ketahanan ekonomi negara. Namun, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik mencapai swasembada pangan dan energi, terutama terkait penggunaan lahan. Pembukaan hutan untuk lahan pangan atau energi seluas 4,5 juta hektar saja akan menghasilkan emisi GRK sebesar 2,59 miliar ton CO2-ek (Trend Asia, 2025). Artinya, jika 9,2 juta hektar lahan hutan dibuka untuk memenuhi kebutuhan biodiesel B50, emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer setidaknya akan mencapai 5,3 miliar ton CO2-ek.
Selain itu, penggunaan lahan untuk meningkatkan produksi biodiesel dapat memicu persaingan penggunaan lahan dengan sektor lain, seperti pertanian, pemukiman, dan kawasan konservasi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga seringkali mengancam lahan milik masyarakat adat yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian, sumber pangan, dan tempat tinggal. Konversi hutan menjadi kebun sawit dengan sistem monokultur[1] selain menimbulkan deforestasi, juga berpotensi pada penurunan keragaman jenis biodiversitas, hilangnya keanekaragaman hayati serta mengganggu fungsi ekologis.

Memastikan Tercapainya Swasembada Melalui SNDC yang Lebih Ambisius
Swasembada pangan dan energi yang menjadi salah satu misi Presiden Prabowo memang menjanjikan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan memperkuat ketahanan nasional. Namun, konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan ini juga perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama kaitannya dengan target penurunan emisi GRK Indonesia yang baru – SNDC – yang diharapkan lebih ambisius dari sebelumnya.
Mewujudkan swasembada pangan dan energi juga perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, dengan meminimalkan emisi GRK agar tetap selaras dengan upaya global untuk mencegah kenaikan temperatur rata-rata global tidak melebihi 1,5oC. Dalam konteks ini, maka pembukaan lahan hutan primer harus dihindari dan lebih memanfaatkan lahan terdegradasi yang memiliki emisi lebih rendah agar ekosistem hutan tetap terjaga. Selain itu, perlu juga memastikan agar hak-hak masyarakat di sekitar hutan terpenuhi, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan programterkait swasembada pangan dan energi.
Pada akhirnya, Indonesia harus dapat mewujudkan swasembada pangan dan energi tanpa mengurangi ambisi Indonesia dalam menurunkan emisi GRK serta implementasi aksi iklim lainnya. Oleh karena itu, SNDC Indonesia harus dapat mencerminkan keterkaitan antara pencapaian swasembada pangan dan energi melalui implementasi aksi iklim, sehingga dapat menyelaraskan kebijakan penurunan emisi GRK di sektor pangan, energi dan sektor forestry and other land use (FOLU) yang diimplementasikan secara berkeadilan.
[1] Monokultur adalah sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman di lahan yang sama selama beberapa musim tanam
Bagikan :