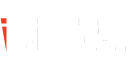Setelah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 98/2021 untuk mengimplementasikan Nationally Determined Contribution (NDC). Peraturan ini mengatur peran daerah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang disampaikan melalui NDC. Namun, pemahaman terkait kesiapan daerah sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam melakukan aksi-aksi iklimnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
Menyadari pentingnya peran daerah dalam menyelaraskan pembangunan dengan tujuan Persetujuan Paris, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Yayasan PIKUL telah melakukan diskusi multipihak, terkait peluang dan tantangan aksi iklim di Sulawesi Tengah (Sulteng), yang berfokus pada sektor pangan sebagai sektor kunci dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Diskusi ini berlangsung pada tanggal 17 Februari 2025, bertempat di kota Palu, Sulawesi Tengah.

Perkembangan Sektor Pangan Sulawesi Tengah
Pemerintah Sulteng menetapkan enam agenda prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan enam agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu agenda tersebut adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya, yang juga menjadi peluang bagi Sulteng untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang menjadi andalan daerah.
Pada tahun 2024, produksi padi berupa gabah kering giling (GKG)[1] di Provinsi Sulteng mencapai 770.030 ton, dengan produktivitas rata-rata 4,42 ton per hektar per tahun (Bappeda Sulteng, 2025). Angka ini masih tergolong rendah, bahkan jika dibandingkan dengan produksi GKG setingkat kota, seperti Kota Makassar, yang mencapai 8 ton per hektar per tahun. Sebanyak 461.205 ton dari produksi gabah tersebut, telah diolah menjadi beras, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sulteng yang hanya berkisar 312.175 ton (100 kg per kapita) per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus sebesar 149.030 ton beras per tahun (Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulteng, 2025).
Provinsi Sulteng juga memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, didukung oleh wilayah perairan seluas 74.452,37 km², serta keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Wilayah ini juga termasuk dalam empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia[2]. Produksi perikanan tangkap Provinsi Sulteng pada tahun 2024 mencapai 132.730,5 ton, sementara produksi perikanan budi daya tercatat lebih tinggi dengan jumlah 252.153,84 ton pada triwulan ketiga (Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, 2025). Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan bergizi, pemerintah daerah berfokus pada peningkatan produksi perikanan tangkap, khususnya perikanan laut, serta pengembangan perikanan budi daya. Selain itu, dilakukan juga upaya perluasan kawasan konservasi perairan laut seluas 1,3 juta hektar yang tersebar di empat (4) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)[3]. Di sektor pertanian, pemerintah daerah telah menetapkan target produksi tanaman pangan dan holtikultura hingga tahun 2029, khususnya untuk beberapa tanaman pangan utama[4].
Tantangan dan Hambatan Sektor Pangan Sulawesi Tengah
Dalam perkembangannya, sektor pertanian di Provinsi Sulteng masih menghadapi berbagai permasalahan krusial. Misalnya seperti, produktivitas yang rendah disebabkan oleh adanya keterbatasan modal para petani—sekitar 46% petani masuk dalam golongan miskin—serta rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)[5] akibat biaya pengeluaran untuk pupuk dan insektisida melebihi pendapatan mereka. Selain itu, tantangan lain adalah minimnya regenerasi petani; sekitar 66% petani berusia di atas 50 tahun, sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih rendah. Alih fungsi lahan yang terus meningkat turut memperparah situasi. Di sisi lain, regulasi yang membatasi pemerintah daerah dalam pengadaan langsung pupuk dan insektisida juga menjadi permasalahan yang mendesak; padahal kebutuhan pupuk urea pada 2024 mencapai 110.000 ton, namun ketersediaannya hanya 51.000 ton.
Sektor perairan dan perikanan di Provinsi Sulteng juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utamanya adalah terbatasnya perluasan kawasan konservasi laut untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistem perairan. Selain itu, implementasi perikanan tangkap terukur berbasis kuota dan zona juga menjadi isu penting dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Pengembangan perikanan budi daya, baik di laut maupun darat, perlu diarahkan pada pendekatan ramah lingkungan agar peningkatan produksi perikanan tidak merusak ekosistem. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu diperlukan untuk mencegah degradasi lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Penanganan sampah laut juga menjadi perhatian khusus, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem laut dan kesehatan masyarakat.
Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pangan dan Gizi di Sulawesi Tengah
Dampak perubahan iklim juga mengancam ketahanan sektor pangan di Provinsi Sulteng. Sebagai sektor dengan penyumbang emisi GRK terbesar – terutama dari gas metana dan penggunaan pupuk sintetis seperti urea – upaya aksi iklim sektor pertanian perlu diperhatikan karena dampaknya juga mengancam sektor pertanian itu sendiri. Meningkatnya suhu udara serta curah hujan yang tidak menentu telah menghambat pertumbuhan tanaman serta menurunkan hasil panen komoditas pertanian, seperti jagung, sayuran, padi, dan buah-buahan. Selain itu, dampak perubahan iklim juga menyebabkan pergeseran kalender tanam, sehingga memperbesar risiko gagal panen di wilayah Sulteng.
Pada sektor perikanan, peningkatan suhu air laut telah berdampak pada populasi ikan dan menurunnya produktivitas perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan juga berdampak pada kegagalan panen dan penurunan produksi perikanan. Situasi ini akhirnya menyebabkan kelangkaan pangan, peningkatan harga, penurunan daya beli masyarakat, serta memperbesar risiko kerentanan pangan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.
Penurunan kualitas hasil panen dan produksi perikanan juga berdampak pada kebutuhan gizi masyarakat, sehingga memicu kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin A, dan yodium. Fluktuasi produksi dan harga pangan akibat pasokan yang tidak stabil juga meningkatkan potensi krisis pangan Sulteng di masa depan. Selain itu, perubahan arus laut, peningkatan keasaman (pH) air, dan variasi tingkat salinitas[6] turut mengganggu stabilitas ekosistem laut. Kenaikan permukaan air laut juga mengancam ekosistem pesisir seperti hutan bakau dan terumbu karang, yang berpotensi mengalami kerusakan atau penurunan luas secara signifikan.
[1] Hasil panen padi dalam bentuk gabah yang telah dikeringkan (kadar air ±14%) dan siap digiling menjadi beras.
[2] WPP 713 (Selat Makassar), WPP 714 (Teluk Tolo), WPP 715 (Teluk Tomini), dan WPP 716 (Laut Sulawesi).
[3] KKP3K Doboto (meliputi wilayah Kabupaten Donggala, Buol, dan Tolitoli); KKP3K Tomini (meliputi Parigi, Poso, dan Tojo Unauna); KKP3K Banggai (meliputi Banggai Laut dan Banggai Kepulauan); serta KKP3K Morowali (meliputi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara).
[4] Padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
[5] Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani.
[6] Salinitas adalah kadar atau tingkat keasinan pada air (konteks dalam artikel ini merujuk pada air laut) yang disebabkan oleh adanya garam yang terlarut di dalamnya.
Bagikan :