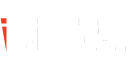Pendanaan iklim menjadi elemen yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan lingkungan dalam beradaptasi akibat dampak perubahan iklim. Pada COP16 tahun 2010 di Cancun, Meksiko, para Pihak menyepakati pembentukan Green Climate Fund (GCF) sebagai salah satu mekanisme pendanaan iklim untuk mendukung negara-negara berkembang melakukan implementasi aksi iklim, termasuk Indonesia. Meski demikian, implementasi GCF dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat nasional, seperti akses pendanaan kelompok masyarakat yang masih sangat terbatas, mekanisme serta implementasi proyek yang kurang transparan, serta minimnya pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat di lokasi proyek yang dituju. Aksi! melihat bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai GCF itu sendiri.
Pada tanggal 31 Agustus 2025, Aksi! menyelenggarakan lokakarya mengenai peran GCF dalam upaya dekarbonisasi di Indonesia, yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkepentingan. Termasuk di dalam pembahasan tersebut adalah peluang akses, serta pemantauan dana GCF dan dampaknya pada masyarakat sekitar. Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) turut berpartisipasi dalam lokakarya tersebut, berbagi pengetahuan utamanya mengenai pembahasan pendanaan iklim dalam kerangka UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).
Pendanaan Iklim dalam Kerangka UNFCCC
Walaupun agenda terkait pendanaan iklim yang dibahas pada COP terhitung sangat banyak, namun semuanya saling terkait dan mendukung satu sama lain. Mulai dari besaran target pendanaan (Long-term Finance dan New Collective Quantified Goal), hingga mekanisme pelaporan (Pasal 9.5 Persetujuan Paris dan Pasal 9.7 Persetujuan Paris). Upaya penelusuran pencapaian target yang terekam dalam Biennial Assessment (agenda dua tahunan di bawah Matters Related to Standing Committee on Finance (SCF)) juga menjadi salah satu agenda penting untuk mengetahui berapa dana iklim yang telah disalurkan. Aliran pendanaan yang disalurkan melalui entitas operasional pendanaan di bawah UNFCCC, seperti Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) dan Adaptation Fund (AF), juga menjadi agenda yang akan dibahas pada perundingan iklim dalam kerangka UNFCCC, termasuk pada COP30 mendatang. Itu sebabnya, penting bagi kelompok masyarakat sipil untuk memahami bagaimana negosiasi pendanaan iklim di bawah UNFCCC berlangsung. Termasuk di dalamnya peran GCF dalam membantu negara-negara berkembang untuk melakukan implementasi iklim, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas negara-negara tersebut.
Tantangan Pendanaan Iklim
Meskipunpendanaan iklim multilateral, seperti GCF, sudah mulai terbentuk, akan tetapi setelah hampir 14 tahun berjalan, penyaluran dana iklim untuk membantu negara-negara berkembang masih menemukan berbagai tantangan. Pertama, sampai saat ini, belum ada definisi yang disepakati bersama terkait dengan pendanaan iklim (climate finance). Kerangka pelaporan yang digunakan oleh para Pihak dalam konteks Persetujuan Paris, Enhanced Transparency Framework (ETF), masih memberikan otoritas kepada masing-masing Pihak untuk mendefinisikan pendanaan iklim. Tentu saja, tanpa kesepakatan yang jelas, para Pihak memiliki definisi pendanaan iklim yang berbeda. Hal ini akhirnya berdampak pada adanya perbedaan penelusuran pendanaan iklim yang dilakukan oleh negara kontributor dan negara penerima.
Kedua, masih terbatasnya akses pada pendanaan iklim, khususnya untuk negara-negara berkembang. Mengakses dana GCF, contohnya, memerlukan entitas terakreditasi yang proses akreditasinya memerlukan waktu dan energi yang sangat besar. Bukan hanya memerlukan waktu yang sangat lama, namun ketentuan untuk memenuhi fiduciary standard[1]serta environment and social safeguard oleh entitas terakreditasi masih sangat rumit dan kompleks untuk dipenuhi entitas nasional. Kemampuan untuk menyusun proposal juga menjadi hambatan yang belum dapat teratasi. Oleh karena itu, bagi entitas-entitas yang memiliki akses langsung pada GCF, diperlukan program peningkatan kapasitas guna mengatasi masalah-masalah tersebut.
Ruang Gerak Kelompok Masyarakat Sipil dalam Konteks GCF
Terdapat ruang yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mempengaruhi gerak GCF. Pertama, melalui proses pengambilan keputusan para Pihak di COP. Sebagai entitas yang dibentuk oleh COP (Conference of the Parties), maka GCF harus mematuhi panduan yang diberikan oleh para Pihak di COP. Setiap tahunnya, GCF harus melaporkan kepada COP terkait perkembangan yang dicapai oleh GCF terhadap mandat yang diberikan oleh COP kepada GCF.
Selain COP, ruang gerak lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil adalah board meeting GCF. Walau demikian, board meeting GCF ini bersifat sangat teknis dan memerlukan pengetahuan-pengetahuan teknis bukan hanya yang terkait dengan pendanaan namun juga pembiayaan iklim. Misalnya proses akreditasi, penentuan standar fidusiari yang perlu dipenuhi, penggunaan instrumen equity, concessional loan, dan lain sebagainya.
Kelompok masyarakat sipil juga dapat bekerja pada tingkat nasional, melalui interaksi dengan National Designated Authority (NDA) dan Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan masukan pada proses pengeluaran ‘No Objection Letter’ (NOL)[2] bagi entitas terakreditasi yang ingin menyampaikan proposal pada GCF. Tanpa adanya informasi yang mendalam terkait dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan, maka sangat memungkinkan bagi NDA untuk mengeluarkan NOL tanpa adanya evaluasi yang lebih dalam.
Peran subnasional menjadi sangat penting terkait dengan implementasi aksi iklim. Hal ini dikarenakan, semua aksi iklim pasti memerlukan ruang dan ruang tersebut akan terkait dengan peran daerah. Namun, upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas di subnasional, baik pemerintah maupun aktor-aktor non-pemerintah di daerah, mengenai aksi iklim itu sendiri.
Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui interaksi dengan Accredited Entities[3]yang dapat mengakses pendanaan iklim multilateral, seperti GCF. Memastikan adanya interaksi dengan entitas terakreditasi, akan meningkatkan kemungkinan bagi entitas terakreditasi untuk melibatkan kelompok masyarakat sipil serta komunitas terdampak yang tepat.
Melakukan Advokasi terkait GCF
Melakukan advokasi terkait pendanaan iklim, seperti GCF, memerlukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait isu. Mengerti instrumen tata kelola GCF (Governing Instrument GCF), menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan dapat digali melalui riset, namun pemahaman perlu dibangun secara konsisten. Oleh karena itu, memiliki ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai isu pendanaan iklim, khususnya GCF, perlu ditingkatkan guna membangun pemahaman yang kuat.
Membangun jaringan yang menghubungkan kelompok masyarakat sipil yang bergerak di perundingan iklim global dengan kelompok masyarakat sipil di tingkat tapak, akan memperkaya pengetahuan masing-masing kelompok, sehingga dapat menyusun pesan advokasi berbasis bukti (evidence based) untuk memastikan aliran pendanaan iklim sampai ke kelompok masyarakat terdampak.
[1] Fiduciary standard adalah standar keuangan dan tata kelola yang mengikat bagi setiap entitas yang bekerja sama dengan Green Climate Fund (GCF).
[2] No objection letter adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh National Designated Authority (NDA) yang menyatakan tidak keberatan terhadap proposal pendanaan iklim yang diajukan, misalnya kepada GCF. NOL juga sering menjadi penanda bahwa proposal tersebut selaras dengan prioritas negara tersebut terkait perubahan iklim.
[3] Accredited Entities adalah lembaa-lembaga yang telah terakreditasi oleh GCF untuk menyalurkan pendanaan iklim.
Bagikan :