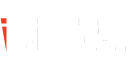Panas ekstrem menjadi risiko iklim yang semakin memengaruhi kesehatan masyarakat, produktivitas pekerja, serta stabilitas ekonomi di negara-negara Asia Pasifik. Dalam Technical Report and Guidance: Climate Change and Workplace Heat Stress (2025) oleh World Health Organization (WHO) dan World Meteorological Organization (WMO), sekitar 2,4 miliar pekerja dunia—termasuk 1,5 miliar di Asia Pasifik—sudah terpapar panas ekstrem yang menyebabkan penurunan kesehatan dan produktivitas kerja mereka. Produktivitas pekerja menurun sebesar 2–3% untuk setiap kenaikan 1°C di atas 20°C dalam indeks Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)[1]. Kawasan Asia—wilayah dengan laju pemanasan tercepat kedua di dunia setelah Eropa—kini menghadapi peningkatan risiko panas ekstrem yang semakin intens dan meluas. Bahkan dalam skenario pemanasan global 1,5°C, puluhan juta orang di kawasan Asia diperkirakan hidup dalam kondisi stress panas sedang hingga sangat tinggi. Lebih dari itu, sebagian besar kejadian cedera kerja dan penyakit akibat panas, justru terjadi di luar periode gelombang panas. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko panas bersifat kronis dan membutuhkan strategi adaptasi yang lebih komprehensif dari sekadar pendekatan reaktif berbasis peringatan gelombang panas.

Strategi Adaptasi Panas Ekstrem
Diskusi terkait heat resilience di 9th Asia Pacific Adaptation Network Forum di Bangkok lalu menggarisbawahi kebutuhan akan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan kebijakan, sains, teknologi, pembiayaan, dan tata kelola dalam upaya melakukan adaptasi terhadap panas ekstrem. Salah satu strategi yang paling mendesak adalah penguatan sistem peringatan dini panas yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengaktifkan tindakan otomatis ketika suhu mencapai ambang batas risiko. Berbagai mekanisme, seperti threshold-based financing[2], Prosedur Operasional Standar (Standarad Operational Procedure/SOP) lintas sektor, serta paket minimum layanan kesehatan, dianggap penting untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu, penggunaan indikator yang lebih akurat, seperti WBGT, sangat krusial untuk menilai risiko kesehatan pekerja luar ruang, seperti petani, nelayan, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan.
Upaya adaptasi terhadap panas ekstrem juga harus diperkuat melalui perencanaan kota dan penggunaan infrastruktur hijau. Penerapan Nature-Based Solutions (NBS)[3] sebagai strategi pendinginan alami yang dapat menurunkan suhu panas yang tersimpan pada material fisik perkotaan – seperti jalan, atap bangunan, dinding luar, dan ruang publik – perlu dilakukan secara signifikan. Revitalisasi sungai[4], perluasan ruang hijau, peningkatan tutupan pohon, penggunaan permukaan reflektif[5], dan desain ruang publik yang menyediakan zona sejuk adalah contoh intervensi yang dapat langsung dirasakan manfaatnya. Hong Kong membuktikan bahwa setelah melakukan rehabilitasi terhadap 200 sungai dan ruang biru, temperatur lokal terbuktimengalami penurunan hingga 3,5–5°C. Pembelajaran ini menegaskan bahwa peran NBS bukan lagi sebagai pelengkap, namun sejak awal harus dirancang sebagai bagian dari infrastruktur kota.
Penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), sistem pemantauan panas, dan pemodelan spasial, dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memperkuat respons adaptasi, namun tetap tidak dapat berdiri sendiri. Dampak panas akan berbeda antar wilayah dan kelompok masyarakat, sehingga adaptasi hanya efektif jika dikombinasikan dengan penguatan kapasitas lokal dan tata kelola inklusif. Itu sebabnya, keberhasilan adaptasi tidak diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan dari siapa yang memperoleh manfaatnya dan sejauh mana teknologi tersebut dapat diakses oleh kelompok rentan, seperti masyarakat pedesaan, pekerja migran, dan penduduk lansia.

Relevansi dengan Pembangunan Berkelanjutan
Beberapa pembelajaran dari negara-negara di kawasan Asia memiliki relevansi kuat bagi arah pembangunan berkelanjutan Indonesia. Pertama, risiko panas ekstrem berkaitan erat dengan isu ketenagakerjaan, kesehatan, energi, dan produktivitas nasional. Pekerja informal—petani, nelayan, buruh konstruksi, dan pedagang—adalah kelompok yang paling terdampak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional. Itu sebabnya, penyusunan Heat Action Plan (HAP), baik di tingkat nasional maupun daerah, menjadi kebutuhan yang mendesak. HAP dapat berisi sistem peringatan dini berbasis WBGT, perlindungan pekerja ketika puncak panas terjadi, SOP sektor kesehatan, serta mekanisme koordinasi antara lembaga teknis yang relevan. Pada konteks Indonesia, lembaga teknis yang dimaksud antara lain adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah.
Kedua, upaya adaptasi terhadap panas ekstrem harus sejalan dengan agenda pembangunan kota berkelanjutan. Integrasi NBS dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat membantu untuk mengurangi suhu dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini meliputi target tutupan pohon minimum, zonasi ruang biru sebagai pendingin alami, desain permukaan reflektif, serta revitalisasi sungai di kota-kota besar dan menengah. Pendekatan ini bukan hanya merupakan upaya adaptasi, tetapi juga upaya untuk mendukung kualitas udara yang lebih baik.
Ketiga, pembiayaan upaya adaptasi terhadap panas ekstrem membutuhkan inovasi. Ketiadaan pendapatan finansial langsung dari upaya-upaya adaptasi terhadap panas ekstrem menjadikan peran Pemerintah untuk melakukan de-risking[6] menjadi penting untuk menarik investasi swasta. Upaya derisking ini dapat dilakukan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Asian Development Bank (ADB) juga menyoroti gagasan Heat Bond[7] yang dapat diterbitkan untuk meningkatkan kesadaran publik sekaligus membuka sumber pendanaan baru. Kombinasi pendanaan filantropi, dana publik, dan investasi swasta dapat menciptakan skala pembiayaan yang lebih besar dan berkelanjutan.
Akhirnya, integrasi keadilan sosial juga ditekankan agar upaya adaptasi terhadap panas ekstrem tidak memperbesar ketimpangan. Kelompok paling terdampak seharusnya tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari perencana solusi. Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai co-creator, serta memastikan bahwa teknologi dan intervensi benar-benar dapat diakses dan digunakan oleh semua kelompok, akan menentukan keberhasilan adaptasi jangka panjang. Dengan mengadopsi pembelajaran dari negara-negara di kawasan Asia, Indonesia dapat mempercepat langkah menuju pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di tengah kenaikan suhu global.
[1] Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) mengukur kombinasi suhu udara, kelembapan, radiasi matahari, dan kecepatan angin. WBGT lebih mampu menggambarkan beban panas fisiologis pada tubuh manusia dibanding sekadar suhu udara.
[2] Threshold-based financing adalah skema pendanaan yang tidak menunggu bencana terjadi, namun dapat diaktifkan secara otomatis ketika indikator tertentu menunjukkan bahwa risiko bencana meningkat.
[3] Nature-Based Solutions adalah pendekatan penanganan perubahan iklim yang memanfaatkan fungsi dan proses alam untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan masyarakat.
[4] Revitalisasi sungai merupakan pemulihan fungsi ekologis dan sosial sungai melalui perbaikan kualitas air, rehabilitasi bantaran, dan penataan ruang agar berkelanjutan.
[5] Intervensi perkotaan untuk mengurangi panas melalui material dengan albedo tinggi yang memantulkan kembali panas matahari.
[6] De-risking adalah peran Pemerintah dalam mengurangi risiko investasi—misalnya melalui jaminan, pembiayaan awal, atau insentif—agar sektor swasta bersedia berinvestasi dalam proyek iklim yang dinilai tinggi risiko atau rendah keuntungan langsung.
[7] Heat Bond merupakan instrumen pembiayaan, seperti green bond yang diterbitkan untuk mendanai proyek heat resilience termasuk infrastruktur peneduhan kota, pendinginan pasif bangunan, ruang hijau, atau intervensi penanganan gelombang panas di perkotaan.
Bagikan :