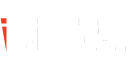Pada tahun 2021, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disampaikan ke UNFCCC. Berdasarkan Perpres ini, daerah memiliki peluang untuk berkontribusi dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang telah ditetapkan melalui NDC.
Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki keunggulan berupa kawasan hutan, destinasi pariwisata, serta kawasan industri yang berkembang, termasuk nikel. Jika dikelola dengan optimal, industri nikel dapat berkontribusi secara signifikan dalam transisi energi nasional. Hal ini disebabkan karena produksi nikel dapat dimanfaatkan sebagai material pendukung infrastruktur energi terbarukan, seperti baterai.
Itu sebabnya, menyelaraskan aksi iklim yang dilakukan di daerah dengan upaya Indonesia untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan Persetujuan Paris, menjadi penting. Oleh karena itu, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Yayasan Pikul dan Walhi Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Desember 2024 di Palu, Sulawesi Tengah, mengadakan diskusi publik yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat sipil untuk memastikan peran daerah dalam melakukan aksi iklim secara berkeadilan.
Isu degradasi lingkungan di Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah memiliki potensi untuk menurunkan emisi GRK, namun juga rentan terhadap dampak perubahan iklim. Industri nikel yang marak di provinsi ini, terutama di desa seperti Tompira, Momino, dan Molores di Morowali Utara, menyebabkan degradasi lingkungan di daratan dan pesisir Sulawesi Tengah. Aktivitas tambang, termasuk operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), diduga memengaruhi cuaca dan memperburuk kondisi lingkungan. Hal ini terbukti dari sungai yang semula jernih dan menjadi sumber air masyarakat, kini sudah menjadi keruh. Terjadinya peningkatan intensitas banjir yang tidak dapat diprediksi dari tahun ke tahun juga semakin mengancam kehidupan masyarakat.
Di kawasan pesisir, degradasi lingkungan diperparah oleh limpahan limbah industri dari hulu yang mencemari ekosistem laut, merusak kualitas air, mengganggu kehidupan biota laut, serta mengancam sumber penghidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut. Contohnya, pada kelompok perempuan yang membudidayakan kerang meti, saat ini terpaksa menanggung biaya tambahan karena harus membersihkan pasir tambang yang mengendap di habitat kerang. Hal ini diakibatkan oleh pasir tambang yang terbawa arus laut dan merusak kualitas hasil tangkapan.
Meningkatnya pembangunan pelabuhan dan permukiman, serta konversi lahan mangrove menjadi lahan tambak, juga menjadi penyebab degradasi lingkungan di kawasan pesisir, di Kabupaten Donggala. Salah satu dampak yang terlihat adalah terjadinya intrusi air laut sampai ke permukiman dan mencemari sawah atau lahan pertanian warga setempat. Degradasi lingkungan di kawasan pesisir juga menyebabkan hilangnya beberapa permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Tosale, karena sudah tertutupi oleh air laut. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya menghancurkan permukiman, tetapi juga mata pencaharian masyarakat, terutama nelayan, akibat cuaca yang tidak menentu serta kondisi lingkungan yang memburuk.
Peralihan komoditas utama petani di Sulawesi Tengah
Pola cuaca yang tidak dapat diprediksi akibat perubahan iklim di Sulawesi Tengah, mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen pada komoditas padi dan jagung. Seperti yang terjadi di Poso, untuk beralih ke tanaman lain, petani harus menggunakan lahan yang sebagian besar merupakan tanah bertekstur basah atau rawa, sehingga hanya cocok ditanami kakao dan durian. Sedangkan, sebagian besar wilayah mereka juga berada di tengah kawasan taman nasional, di mana pengelolaan sumber daya oleh masyarakat terbatas – seperti pengambilan kayu atau hasil hutan lainnya – serta memerlukan izin dari Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL). Oleh karena itu, pilihan petani untuk memproduksi tanaman pangan menjadi terbatas karena adanya keterbatasan lahan tanam.
Kehadiran perkebunan sawit di Morowali juga mendorong banyak masyarakat beralih dari menanam kakao, cengkeh, dan pala menjadi sawit karena dianggap sebagai komoditas yang lebih menjanjikan. Tanaman kakao memiliki risiko tinggi terhadap serangan penyakit, seperti kanker batang dan kanker buah, serta lebih sulit dalam budidaya hingga pasca panen. Sebaliknya, sawit lebih mudah dibudidayakan karena minim risiko penyakit dan biaya produksi yang relatif lebih rendah. Hingga berumur 10 tahun, sawit terbukti dapat menghemat biaya produksi petani, sehingga menjadi komoditas andalan. Namun, dampak negatif budidaya sawit secara monokultur terhadap tanaman lain dan lingkungan di sekitarnya sering diabaikan, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak tersebut.
Pentingnya peran Organisasi Masyarakat Sipil dan kolaborasi bersama
Bagi pemerintah daerah, OMS berkontribusi dalam mendukung implementasi kebijakan melalui kegiatan advokasi, misalnya advokasi moratorium terhadap perusahaan yang merusak lingkungan. OMS juga aktif melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan terkait wawasan iklim dan lingkungan. Kegiatan advokasi tidak hanya terfokus di tingkat pemerintah daerah, beberapa OMS juga terlibat dalam advokasi kebijakan lingkungan pada kelompok perempuan.
Bagi organisasi lokal, OMS berperan dalam penguatan kapasitas dan keterampilan organisasi lokal, misalnya untuk melakukan riset aksi dan kampanye. Bagi masyarakat, OMS berperan penting dalam berbagai kegiatan penguatan partisipasi masyarakat di lingkar tambang dan pemberdayaan, seperti:
- Pembentukan balai kegiatan belajar masyarakat;
- Penyebaran informasi dan edukasi melalu pamflet dan media lainnya;
- Peningkatan pengetahuan bagi petani dan nelayan di sekitar kawasan industri;
- Penguatan kelompok pemuda, karang taruna, dan perempuan, serta melalui majelis taklim atau kelompok ibadah;
- Pembentukan serikat pekerja untuk memperkuat solidaritas komunitas; serta
- Pelatihan pengolahan produk lokal untuk mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Upaya-upaya tersebut juga perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk jurnalis dan komunitas media sosial. Pemanfaatan platform seperti jurnalisme warga, penting dilakukan untuk menyuarakan isu-isu lingkungan di tingkat lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, kolaborasi berbagai pihak juga perlu diperkuat sebagai landasan penting dalam meningkatkan ketahanan sosial-ekologis di Sulawesi Tengah.
Bagikan :