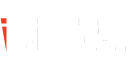Sebagai provinsi kepulauan dengan ekosistem darat dan laut yang beragam, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2023, Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) bersama Yayasan Pikul telah melakukan kajian mengenai kesiapan Provinsi NTT dalam menghadapi transisi energi dan menyoroti keterkaitan erat antara transisi energi dengan sektor-sektor lain, utamanya dengan kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), keanekaragaman hayati, serta pangan.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, IRID, Yayasan PIKUL, beserta Pemerintah Provinsi NTT mengadakan diskusi bersama pada hari Rabu, 10 September 2025, guna menggali lebih dalam mengenai keterkaitan antara isu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Selain itu, dibahas juga hal-hal terkait bagaimana kedua isu dan keterkaitannya dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan, khususnya di daerah. Diskusi tersebut memberikan gambaran terkait isu-isu yang penting bagi Provinsi NTT, utamanya yang terkait transisi energi, serta implikasinya terhadap ketahanan energi dan pangan daerah.
Tantangan Transisi Energi dan Tekanan terhadap Ketersediaan Lahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, Provinsi NTT menargetkanpeningkatan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer dari 19,05% pada tahun 2024 menjadi 37,47% pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Provinsi NTT berfokus pada upaya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), karena NTT dinilai sudah sangat siap, baik dari segi potensi ketersediaan sumber energi surya, maupun kesiapan secara teknis. Namun dalam implementasinya, pengembangan energi terbarukan di NTT masih menghadapi tantangan mendasar seperti persoalan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik serta dampaknya terhadap keterbatasan lahan, air, dan kerusakan lingkungan.
Pada sisi ketenagalistrikan, misalnya, arah kebijakan dari pemerintah pusat yang mendorong pembangunan PLTS terpusat di NTT menjadi persoalan tersendiri. Hal ini disebabkan karena pola permukiman dan kondisi geografis di NTT yang cenderung menyebar menjadikan pendekatan tersebut dinilai kurang tepat dan efisien. Transisi energi di NTT juga menghadapi persoalan terkait opsi penggunaan bioenergi.Misalnya, upaya co-firing di PLTU Bolok dinilai belum siap akibat masalah keterbatasan biomassa. Kondisi semi-arid[1] di NTT juga menyebabkan ketersediaan bahan baku untuk biomassa menjadi sangat terbatas karena rendahnya produktivitas lahan dan keterbatasan sumber air. Pendekatan co-firing dinilai lebih cocok dilakukan di daerah dengan industri perkebunan besar, seperti kelapa sawit, dan bukan di wilayah kepulauan kering, seperti NTT. Memaksakan upaya co-firing dinilai justru dapat mendorong pembukaan hutan baru dan berpotensi memperburuk ketahanan pangan, air, dan lingkungan.
Sama halnya dengan biofuel. Upaya produksi biofuel dari komoditas jagung di Pulau Sumba juga sudah pernah diterapkan, namun tidak berjalan karena pemanfaatan jagung berbenturan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Produksi biofuel dikhawatirkan akan mendorong pemanfaatan hutan sebagai sumber penyediaan bahan baku, yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan dan mempercepat degradasi lingkungan. Di sisi lainnya, upaya pengembangan energi panas bumi (geothermal) juga belum menjadi prioritas karena faktor lokasi, akses, dan kesiapan teknis yang masih terbatas.
Selain itu, isu ketersediaan lahan muncul setelah adanya arahan dari pemerintah pusat kepada Provinsi NTT agar menyediakan lahan seluas kurang lebih 331.000 hektar (ha), atau sekitar 6,7% dari total luas daratan NTT, untuk kebutuhan pangan dan energi. Angka tersebut dinilai tidak realistis dan dapat berpotensi menambah tekanan terhadap lahan, hutan, pertanian, serta mengancam ruang hidup masyarakat lokal NTT.
Isu Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan di Wilayah NTT
Isu terkait ketahanan air muncul sebagai tantangan paling mendasar di Provinsi NTT karena ketahanan pangan dan energi sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas sumber daya air. Salah satu upaya penyediaan sumber daya air adalah dengan memanfaatkan embung[2] sebagai penampung air untuk kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pertanian.
Saat ini, di Provinsi NTT terdapat dua jenis embung, yaitu embung kecil dengan kapasitas 25.000-100.000 m3 (1000 embung) dan embung irigasi dengan kapasitas di atas 100.000 m3 (30 embung) (Dinas PUPR NTT, 2025). Pada umumnya, embung kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga dan ternak, sedangkan embung irigasi diperuntukkan bagi kebutuhan irigasi pertanian masyarakat. Sebagian embung dibangun oleh berbagai instansi pelaksana, bukan seluruhnya oleh Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga kualitas dan pengelolaannya tidak selalu seragam.
Akan tetapi, jumlah embung yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakatNTT. Terlebih jika ditambah dengan rencana pembukaan lahan tambahan untuk budi daya tanaman energi dan pangan yang akan meningkatkan kebutuhan irigasi. Kondisi iklim yang kering juga memperburuk situasi ini, karena minimnya curah hujan di wilayah NTT memengaruhi pengisian embung yang berlangsung sangat lambat. Contohnya, seperti embung Raknamo yang baru terisi penuh setelah dua tahun akibat terjadinya badai Seroja pada tahun 2021 lalu. Kemudian, banyak juga embung yang tidak berfungsi optimal karena lokasinya yang kurang terjangkau dari lokasi pemanfaatan embung. Hal ini juga termasuk jarak yang jauh dari lahan pertanian, minimnya pelibatan komunitas setempat, serta keterbatasan dana pengelolaan yang menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan embung.
Kebijakan Terpadu Pangan-Air-Energi Berbasis Konteks Lokal NTT
Rangkaian isu di atas menunjukkan bahwa kebijakan strategis yang dapat mengintegrasikan ketahanan pangan, air, energi, dan kelestarian lingkungan sangat diperlukan. Dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim (RAD-PI) perlu memperkuat pendekatan adaptasi perubahan iklim secara lebih terpadu. Salah satunya melalui pendekatan berbasis pengetahuan lokal, seperti penerapan strategi “menabung air”[3] atau penguatan praktik wanatani (agroforestri)[4] yang telah diterapkan di berbagai tingkat komunitas, dan dapat diadopsi ke dalam kebijakan daerah maupun nasional.
Selain itu, transisi energi di NTT – dan juga provinsi lainnya – juga tidak dapat hanya mengikuti target nasional. Diperlukan pendekatan khusus yang dapat mempertimbangkan kondisi ekologi semi-arid, keterbatasan air, tekanan terhadap lahan, serta pola hidup dan karakter masyarakat kepulauan. Pemanfaatan potensi angin dan surya yang melimpah dinilai lebih relevan dan efisien, dibanding memperpanjang rantai produksi biomassa dan biofuel yang berisiko tinggi mengancam ketahanan pangan dan lingkungan. Pendekatan energi berbasis konteks lokal ini dapat menjadi dasar transisi iklim yang lebih berkeadilan di Provinsi NTT.
[1] “Semi-arid” atau semi-kering adalah iklim yang agak kering, terletak di antara iklim kering dan iklim yang lebih lembap.
[2] Embung adalah kolam atau cekungan buatan yang berfungsi menampung air hujan atau limpasan air dari sumber lain seperti sungai kecil atau mata air. Fungsi utamanya adalah menyimpan air saat musim hujan untuk digunakan sebagai cadangan saat musim kemarau, terutama untuk irigasi pertanian, minum ternak, dan keperluan rumah tangga lainnya.
[3] Strategi “menabung air” adalah upaya konservasi air untuk meningkatkan cadangan air tanah dengan cara menampung dan menyerap air hujan kembali ke tanah.
[4] Wanatani (argoforestri) adalah sistem pengelolaan lahan yang memadukan unsur kehutanan (pepohonan) dan pertanian dalam satu lahan yang sama, dengan tujuan menciptakan pertanian yang berkelanjutan.
Bagikan :