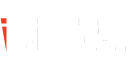Berkah Tersembunyi

Pada tahun 2001, Dusun Kedungrong di Kulon Progo, Yogyakarta, mengalami tanah longsor yang menghancurkan rumah-rumah warga di sekitarnya hingga merenggut korban jiwa. Bantuan datang dari berbagai instansi pasca bencana terjadi, salah satunya dari Universitas Gajah Mada (UGM). Saat mengunjungi lokasi, para akademisi UGM tersebut melihat potensi energi terbarukan berupa arus deras dari saluran irigasi Kali Bawang sepanjang 25 km yang melalui Dusun Kedungrong. Saluran irigasi ini merupakan hasil intake sadap samping[1] terhadap Sungai Progo. Melihat potensi tersebut, akhirnya para akademisi UGM mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Dusun Kedungrong. Usulan diajukan ke pemerintah daerah (Pemda) oleh Bapak Cahyono sebagai perwakilan masyarakat Dusun Kedungrong saat itu. Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo pada tahun 2001 tidak mencukupi untuk membangun PLTMH di Dusun Kedungrong.
Titik Balik

Pada tahun 2004, Bapak Cahyono menjadi wakil rakyat di DPRD Kulon Progo dan kembali mengusulkan pembangunan PLTMH di Dusun Kedungrong. Usulan tersebut disetujui, namun APBD masih tidak mencukupi. Kemudian, anggaran pembangunan PLTMH Kedungrong diajukan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) untuk mendapatkan bantuan. Pada tahun 2009, tim mahasiswa UGM melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Kedungrong, di mana mereka mengembangkan PLTMH sederhana namun belum dapat digunakan secara maksimal. Setahun kemudian, Dusun Kedungrong kembali kedatangan tim mahasiswa UGM lainnya dan berhasil mengembangkan kapasitas PLTMH Kedungrong menjadi 400 VA untuk menyalakan 10 lampu jalan.
Pada tahun 2012, anggaran pembangunan PLTMH Kedungrong yang diusulkan tahun 2004 baru disetujui oleh BBWSSO dan pembangunan pun dimulai. Di tahun yang sama, PLTMH Kedungrong mulai beroperasi hingga saat ini dan dimanfaatkan untuk menyalakan sebanyak 33 lampu jalan, serta memenuhi kebutuhan listrik bagi 55 kepala keluarga (KK) di Dusun Kedungrong. Meski kebutuhan listrik dapat terpenuhi dari PLTMH, masyarakat Dusun Kedungrong tetap mengandalkan listrik PLN sebagai cadangan, dengan komposisi penggunaan listrik 80% bersumber dari PLTMH dan 20% bersumber dari PLN. Penggunaan listrik dari PLN diutamakan untuk mengoperasionalkan perangkat yang rentan terhadap kestabilan arus listrik, sementara PLTMH masih membutuhkan stabilizer untuk menstabilkan arus listrik yang dihasilkan.
Saat ini, PLTMH Kedungrong menggunakan 2 generator sebesar 18 kW yang dipakai secara bergantian dan memiliki Laboratorium Terpadu Mikrohidro sebagai tempat riset dan belajar bagi akademisi dan masyarakat terkait mikrohidro dan energi terbarukan. Meski desain awal PLTMH Kedungrong memiliki muatan listrik sebesar 18 kW, namun PLTMH ini dirancang hingga dapat menghasilkan daya sebesar 500 kW dan memiliki potensi pengembangan hingga 1793 kW.
Transisi Energi Berkeadilan: Pelibatan Komunitas dalam Memastikan Keberlanjutan

Yogyakarta memiliki 10 titik PLTMH, sayangnya sebagian besar tidak beroperasi dengan baik. PLTMH Minggir di Sleman, misalnya, walaupun bangunan PLTMH masih terawat oleh operator yang bertugas, namun tidak dimanfaatkan secara optimal akibat minimnya kesadaran masyarakat setempat tentang penggunaan energi bersih. Ada pula PLTMH Sewon di Bantul yang berakhir mangkrak, akibat pelibatan masyarakat yang minim dan kelembagaan komunitas yang belum terbentuk, sehingga tahap pemeliharaan PLTMH tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, di kasus PLTMH lain, pernah terjadi misinformasi terkait desain bangunan PLTMH yang ternyata berdampak pada penutupan saluran irigasi petani sekitar, sehingga PLTMH ditolak oleh warga setempat dan gagal beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan PLTMH sudah sepatutnya tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial.
Pembelajaran tersebut diadopsi oleh komunitas pengelola PLTMH Kedungrong, yang hingga kini dapat beroperasi dengan baik. Pelibatan masyarakat dalam berbagai tahap pengembangan PLTMH menjadi faktor kunci keberlanjutan proyek ini. Pada tahap pra-konstruksi, pembangunan PLTMH disosialisasikan kepada masyarakat Kedungrong. Sosialisasi tersebut mencakup pengetahuan umum tentang PLTMH, hingga potensi dampak serta manfaat PLTMH bagi masyarakat. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat mengomunikasikan pandangan dan kekhawatirannya, sehingga pembangunan PLTMH dapat memenuhi kebutuhan kelompok penerima manfaat. Itu sebabnya, sosialisasi yang transparan menjadi salah satu prasyarat untuk mendapat penerimaan masyarakat dalam pengadopsian teknologi baru (willingness to agreement), dalam konteks ini adalah PLTMH.
Pada tahap operasional, PLTMH Kedungrong dikelola oleh Komunitas Mikrohidro Terpadu Indonesia (KMTI) Kedungrong. Komunitas ini beranggotakan warga setempat yang memiliki komitmen kuat untuk mengelola PLTMH, baik sebagai operator maupun petugas pemeliharaan. Komitmen tersebut dicerminkan melalui kesediaan untuk belajar dan mengembangkan ilmu terkait mikrohidro, baik terkait pemasangan, operasional, distribusi, pengelolaan, pemeliharaan, serta perbaikan. Mereka juga menjalankan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk berbagi pengetahuan (knowledge-transfer).

Keberlanjutan operasional PLTMH juga tidak dapat dipisahkan dari kesediaan masyarakat yang mendapatkan akses listrik dari PLTMH, untuk membayar iuran (willingness to pay). Iuran sebesar Rp 12.000,00 per KK diharapkan untuk dibayarkan setiap hari Rabu Legi (berdasarkan Kalender Jawa) bersamaan dengan rapat rutin KMTI Kedungrong, untuk mendapatkan akses aliran listrik dari PLTMH tanpa batas atau unlimited. Iuran ini telah mencakup honor untuk operator dan petugas pemeliharaan PLTMH Kedungrong.
Lebih lanjut, KMTI juga terlibat aktif dalam pemeliharaan PLTMH, termasuk membersihkan sampah pada saluran PLTMH setiap sore untuk mencegah gangguan produksi listrik. Komunitas mengakui bahwa tahap pemeliharaan memiliki tantangan tersendiri, terutama tatkala terjadi kerusakan suku cadang PLTMH, yang harganya tidak murah. Sejauh ini, penggantian suku cadang masih dapat dibiayai melalui iuran masyarakat, namun sayangnya iuran tersebut masih belum cukup untuk membeli suku cadang baru dengan kualitas terbaik. Terlebih lagi, suku cadang infrastruktur PLTMH umumnya hanya tersedia di kota-kota besar, sehingga menjadi hambatan tersendiri. Jarak yang jauh dari desa ke kota membuat biaya penggantian suku cadang semakin tinggi.
Pembelajaran dari PLTMH Kedungrong menunjukkan bagaimana pelibatan komunitas setempat dalam kelembagaan proyek energi terbarukan adalah krusial untuk memastikan keberlanjutan. PLTMH Kedungrong yang berbasis komunitas tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengakses energi bersih secara terjangkau, tetapi juga telah memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Listrik dari PLTMH Kedungrong mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat melalui berbagai jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti industri kayu, bengkel las, penjahit, penatu (laundry), penetasan telur, dan usaha pembuatan es kristal, yang baru saja dikembangkan di Desa Kedungrong.
[1] Intake sadap samping, dalam konteks irigasi, adalah bangunan yang terletak di samping saluran utama untuk mengambil air dari saluran utama ke saluran cabang (sekunder atau tersier)
Bagikan :